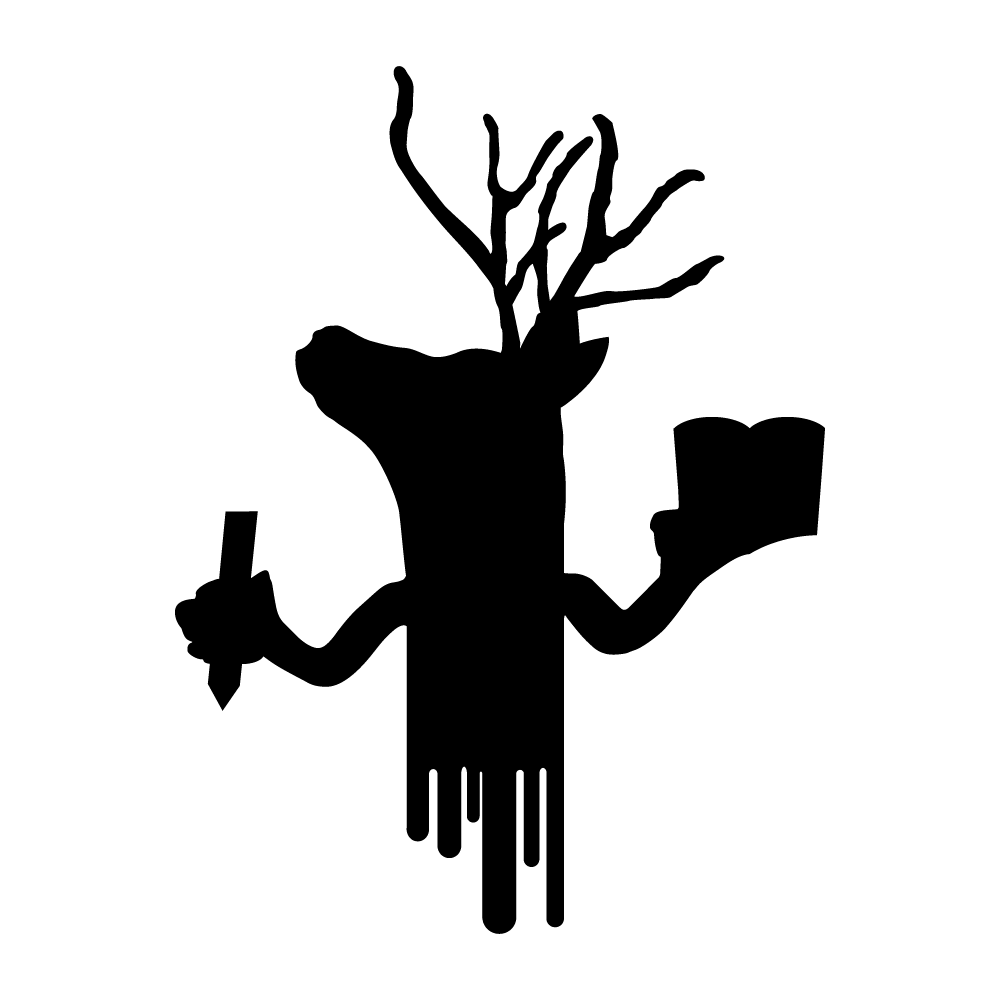Semakin dewasa, semakin banyak tanggung jawab yang datang dari berbagai sisi. Katakanlah dari sisi akademik, kamu pasti merasa semakin tertekan dengan berjalannya waktu, yang menyebabkan kamu mendapatkan tugas-tugas kuliah yang semakin sulit dan variatif. Lalu ketika pulang dari kampus, kamu menemukan bahwa kamar sedang berantakan dan kamu harus merapikannya sendiri, tidak seperti ketika waktu kecil di mana Mama akan membereskannya untukmu. Hal-hal seperti itu mungkin terasa kecil, tetapi ketika sedang dalam kondisi lelah, tak jarang mereka menyebabkan rasa stress semakin menjadi-jadi.
Ketika merasa stress dan berinisiatif untuk menyegarkan pikiran sebentar melalui media sosial, kamu menemukan bahwa teman-teman kamu sedang banyak membuat post tentang capaian prestasi atau organisasi yang mereka ikuti. Tak sadar hal tersebut menyebabkan alam bawah sadar menjadi insecure yang kemudian fenomena FOMO atau fear of missing out mulai terjadi. Kamu mulai merasa kurang dari orang lain sehingga ingin untuk mengejar capaian seperti mereka dengan mengabaikan rasa stress yang tersimpan sejak hari-hari kemarin. Jika fenomena ini dialami oleh banyak orang, maka hal ini juga berkontribusi dalam menciptakan hustle culture di mana orang-orang mengejar kesibukan dengan mengabaikan kesejahteraan atau well-being mereka (Achmad & Lubna, 2023).
Dari interaksi antara berbagai faktor internal dan eksternal di atas, kemudian tak jarang menyebabkan kondisi burned out. Burn out merupakan fenomena di mana kita merasa lelah berkepanjangan secara fisik maupun psikis dari kehidupan sehari-hari hingga terjadi gejala depersonalisasi di mana seseorang mengalami gejala seakan-akan terlepas dari tubuh sendiri (Bianchi et al., 2015). Kondisi burn out memiliki prevalensi yang semakin tinggi seiring dengan perkembangan zaman yang semakin menuntut hasil instan.
Tak jarang, ketika sedang merasa stress berkepanjangan, kita menjadi cenderung menduga-duga kondisi mental yang sedang kita alami karena banyaknya beban yang harus ditanggung. Kemudian berbekal dengan informasi mengenai gejala-gejala gangguan mental yang pernah dibagikan oleh para influencer sosial media, tak sadar kita menjadi bertanya-tanya, “Bukankah yang kualami ini disebut dengan depresi?” Nah, di saat itulah self-diagnose dimulai.
Apa itu self-diagnose dan apakah ada bahayanya?
Self-diagnose merupakan kondisi ketika seseorang menerka-nerka kondisi medis, baik itu fisik maupun psikis, yang sedang dialaminya tanpa rujukan dari dokter atau tenaga medis terkait. Self-diagnose sering terjadi karena membludaknya informasi yang tersedia dari berbagai media sehingga seseorang merasa tidak ada urgensi untuk pergi memeriksakan diri ke rumah sakit karena bekal informasi yang dimiliki sudah cukup untuk membuat hipotesis akan kondisi kesehatannya atau disebut dengan cyberchondria (Zheng et al., 2020).
Self-diagnose secara tidak sadar dapat menyebabkan seseorang menginternalisasikan diagnosis yang dibuatnya sehingga dapat menyebabkan efek nocebo atau suatu keadaan di mana seseorang menjadi sakit karena persepsi negatifnya terhadap suatu hal (Faasse, 2019). Menurut Frisaldi et al. (2015), efek nocebo pada dasarnya merupakan a game of mind yang dihasilkan dari interaksi antara tubuh dengan jiwa.
Jika seseorang membuat self-diagnose mengenai depresi dan terus-terusan “membawa” identitas sebagai orang yang memiliki depresi, maka ia yang sebenarnya tidak depresi lama-kelamaan dapat memilikinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempercayakan kondisi kesehatan pada tenaga medis, bukan pada informasi yang berseliweran di media. Indikatornya, dikutip dari laman Hello Sehat, jika onset gejala depresi terjadi lebih dari tiga minggu secara berturut-turut, mengganggu fungsi dalam keseharian, dan kamu mulai melarikan diri pada hal destruktif, segeralah hubungi fasilitas kesehatan terdekat, ya!
Referensi
Achmad, Z. A., Lubna, P. N. C. (2023). Toxic Positivity Content Uploads on Instagram in Encouraging the Growth of Hustle Culture Gen Z. Journal of Student Academic Research. 9. 1–14. https://doi.org/10.35457/josar.v9i1.2730
Bianchi, R., Schonfeld, I. S., & Laurent, E. (2015). Is it Time to Consider the “Burnout Syndrome” A Distinct Illness?. Frontiers in Public Health. 3. https://doi.org/10.3389/fpubh.2015.00158
Faasse, K. (2019). Nocebo effects in health psychology. Australian Psychologist. 54(6), 453–465. https://doi.org/10.1111/ap.12392
Hello Sehat. (2022, August 20). Lima tanda anda butuh konsultasi psikologi. https://hellosehat.com/mental/stres/apakah-saya-butuh-konsultasi-psikologi/
Zheng, H., Sin, S.-C. J., Kim, H. K., & Theng, Y.-L. (2020). Cyberchondria: a systematic review. Internet Research. 31(2), 677–698. https://doi.org/10.1108/intr-03-2020-0148