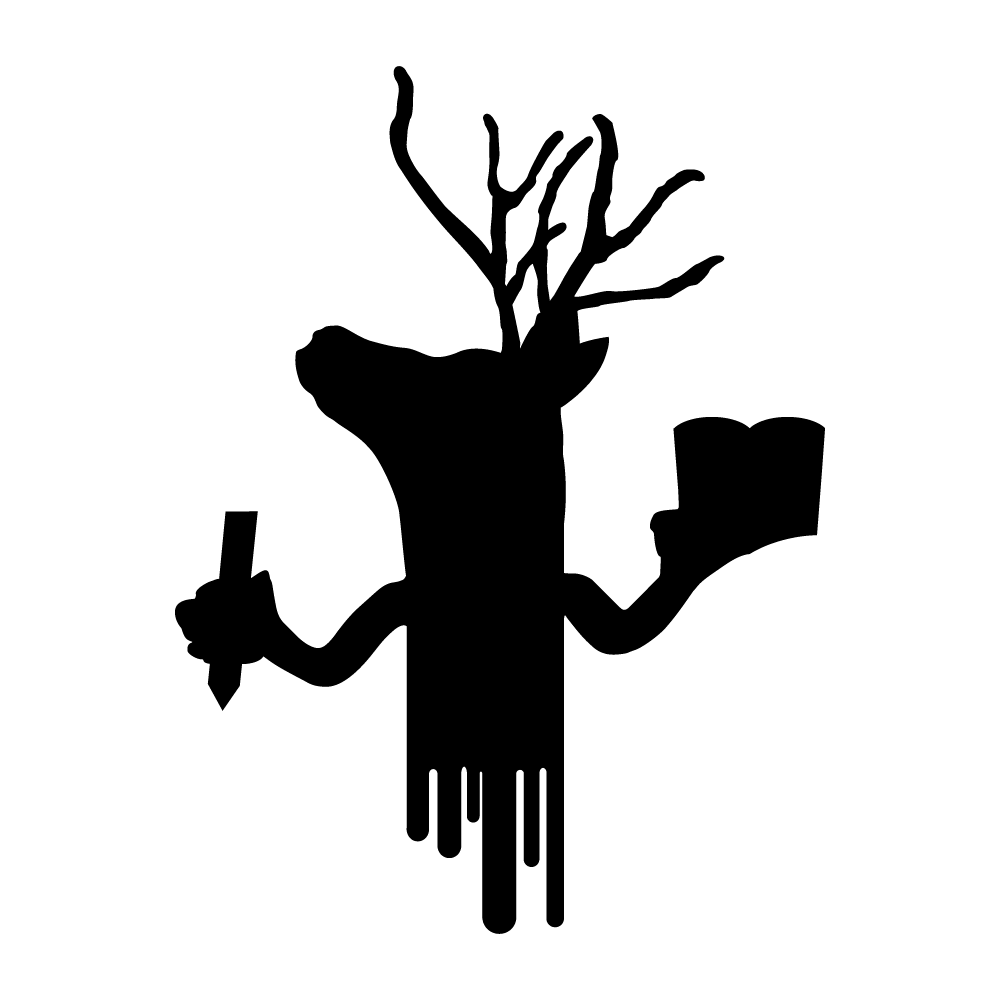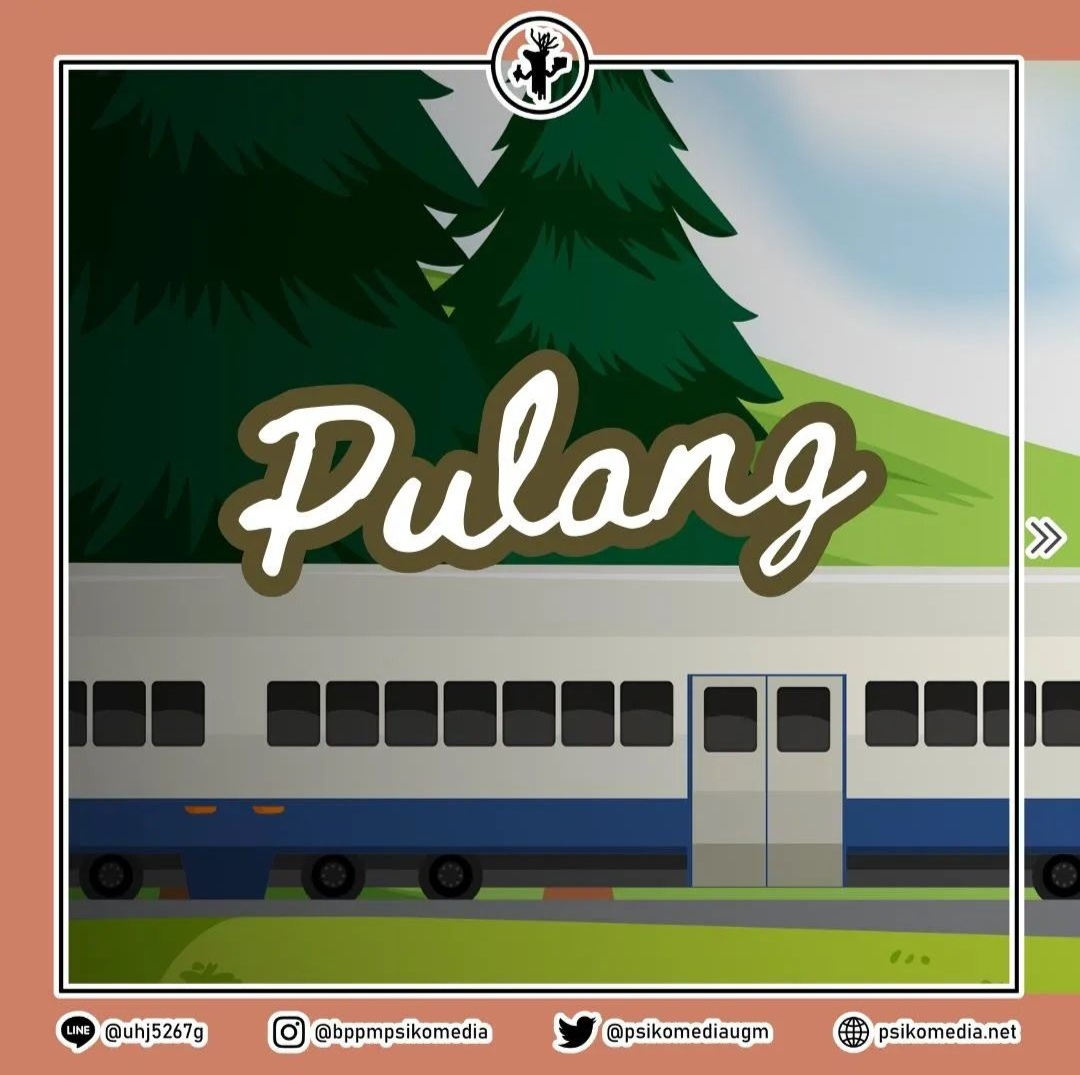Selain membaca, hobiku adalah menggerutu.
Bukan tanpa alasan, sebab hujan yang datang secara mendadak membuatku harus menepi pada angkringan pinggir jalan. Tadinya aku ingin menerobos hujan, membawa basah buku-buku perpustakaan yang kupinjam siang ini. Namun, mengingat masamnya wajah penjaga perpustakaan, aku jadi enggan untuk bersilat lidah tulat nanti–saat ia tahu lembaran buku yang kupinjam bergelombang terkena uap panas pengering rambut. Maka, untuk mengantisipasinya, aku lantas mampir kesini. Angkringan bertenda biru.
Untungnya, saat aku masuk ke dalam tenda, hanya ada satu laki-laki dewasa (entah umur berapa, hanya Tuhan yang tahu) sedang menggulir bebas layar ponselnya. Aman. Tidak akan ada yang menginterupsi waktuku untuk menyendiri—setidaknya sampai rinai hujan mulai ringan. Setelah ibu angkringan melemparkan senyumnya padaku dan kubalas anggukan kecil, aku meletakkan pantatku pada kursi kayu panjang berkaki pendek. Ah, lagi-lagi aku ingin menggerutu sebab badan mungilku tidak bisa mencapai meja angkringan. Namun, tiba-tiba laki-laki dewasa yang sempat kusebutkan tadi memberikan bantalan leher bermotif pandanya padaku.
“Tapi ini untuk leher,” tolakku sesopan mungkin. Aku berjaga-jaga agar tidak mengalami bisulan hanya perkara menduduki bantalan leher imut itu.
Di luar dugaan, ia membalas ujaranku dengan membalikkan badannya dan menunjuk apotek yang terletak di seberang kami. Ia menyengir kuda, melirik etalase apotek seakan berkata, “kalau begitu, tinggal beli salep saja.”
Aku membalas cengiran kudanya dengan cengiran kambing. Tidak lebih lebar, tapi ada rasa tidak nyaman di dalam dada. Namun, apa boleh buat, kata Ibu kita tidak boleh menolak bantuan dari orang lain. Seusai berterima kasih, aku menerima bantalan itu dan menggunakannya sebagai penyangga duduk. Hari ini, benar-benar …
“Bu, saya pesan satu wedang jahe, ya.”
“Jahe saja, Mbak? Atau jahe susu?” Sambil menyiapkan ceret berisi jahe panas, ibu angkringan memastikan apakah pesananku benar atau perlu tambahan. Aku menimbang-nimbang sejenak, menatap pendar lampu minyak yang semakin menguning.
“Jahe saja, Bu.”
Selepas pesananku mendarat, ibu angkringan kembali menata arang dan membuat api di dapur samping. Suasana tenda dalam sesaat terasa canggung: antara aku yang tidak enak hati menduduki bantalan kepala motif panda dan laki-laki dewasa tadi yang hanya sibuk menggulir layar ponselnya. Tidak ada percakapan di antara kami sama sekali. Aku pun memutuskan untuk merenung, mengaduk-aduk wedang jahe bersuhu 365 derajat celcius sambil memikirkan bagaimana caranya pulang dengan cepat sore ini. Aku tahu di rumah Ibu pasti akan mengerti, tapi persendianku tidak. Lengan sekaligus kakiku sudah pegal sejak SKS pertama dimulai.
Tanpa kusadari, tiba-tiba suasana canggung yang kami bangun pecah. Suara berat milik laki-laki dewasa tadi kembali terdengar, persis saat aku baru memikirkan apa yang harus kutulis untuk latar belakang skripsiku. “Pulang kerja, ya, Mbak?”
Aku menyengir. Entah kenapa aku jadi banyak menyengir saat di tenda ini, tapi kurang lebih cengiran kali ini seperti keledai. Aku juga mendadak bisu, bahkan untuk mengungkapkan satu kata pun terasa berat dan asing. Astaga, apakah ini kutukan tenda biru?
“Kuliah semester buyut, Mas. Sedang mengejar skripsi,” balasku terbata. Biarlah terdengar seperti Azis Gagap kalau memang kenyataannya begitu. “Kalau Masnya?”
“Saya pengangguran level medium rare.”
Aku menaikkan alisku heran setelah akhirnya tergelak. Ia juga ikut tergelak—entah apa maksudnya—namun pada akhirnya kami menghabiskan sepersekian detik waktu untuk tergelak bersama. Jangan bilang ini adalah momen ‘how i met your mom’ seperti tren TikTok, karena jelas bukan genre-nya.
“Ya, begitulah. Saya baru dipecat 2 bulan yang lalu. Begini saja tetangga saya sudah heboh, apalagi kalau besok masuk level well done, Mbak.”
Sambil menyesap wedang jaheku, aku mengangguk mengerti. Tidak jauh berbeda, sebab saat ini aku juga sedang diburu oleh kata-kata semacam ‘lulus’ dan ‘skripsi’ sepanjang hari oleh keluarga dan tetangga. Bukannya pelit berbagi progres, tapi aku rasa yang begitu cukup jadi privasi sang empunya.
“Hmm iya juga, ya … lalu, sekarang kesibukan Mas apa?”
“Yaah, tidak jauh dari kamera,” balasnya sambil tersenyum kikuk. Tak lama, tangannya mengeluarkan satu kamera yang aku-tidak-tahu-harganya dan beberapa buku sastra dengan sampul yang sedikit menguning. “Dan membantu teman berjualan buku-buku lama.”
Mataku berbinar terkejut. Buku-buku itu—meskipun warnanya sudah sedikit menguning—sampulnya masih rapi dan tidak ada sobekan sedikitpun. Kalau tidak menjadi penyelam handal, tentu akan susah mendapatkan buku dengan kondisi seapik ini.
“Beberapa buku memang susah dicari, apalagi yang menjadi incaran banyak orang. Tapi, asalkan sudah berkawan baik dengan para penjaja di Shopping Center, semuanya bisa teratasi.”
Seolah-olah membaca pikiranku, ia menerangkan bagaimana cara mendapatkan buku-buku lama itu dengan runtut dan detail. Mulai dari bagaimana cara pemesanannya, dimana letak bandarnya, hingga cara berkawan dengan para penjaja disana. Aku hanya menyimak, sesekali menanggapi namun lebih memenuhi isi obrolan dengan anggukan kepala dan tatapan khidmat.
“Bapaknya baik-baik, bahkan kami ada grup WA untuk berbagi informasi atau sekadar menanyakan stok buku,” ujarnya menutup penjelasan kali ini. “Kalau Mbak ada buku lama yang susah dicari, nanti saya bisa bantu tanyakan di grup. Tenang saja, tidak ada biaya admin.”
Setelah benar-benar mengakhiri penjelasannya, laki-laki dewasa tersebut menenggak kopi pahitnya dengan ekspresi wajah tertentu. Sukar dijelaskan, tapi kutanggapi segalanya dengan senyuman simpul. Umpama hidup di tahun 90-an, aku yakin ia sudah bergabung dengan grup lawak Cagur mewakili Bantul.
“Oh iya!” aku berseru kecil. “Kebetulan saya sedang mencari buku Upacara karya Korrie Layun Rampan. Sewaktu SD, saya merengek pada Bapak untuk dibelikan buku itu sebagai hadiah ulang tahun—tapi sulit untuk menemukannya. Lalu, sekarang saya ingin menggunakannya sebagai bahan referensi utama skripsi. Apakah bisa dibantu?”
“Tentu, saya beberapa kali melihat buku itu di ruko belakang. Nanti saya bantu carikan.”
Aku tersenyum kecil. Rinai hujan sudah mulai berhenti, motor-motor di jalan kudengar sudah bisa melaju cepat tanpa takut tergelincir. Tak lama, beberapa bapak-bapak bermotor bebek terlihat mulai berdatangan dan memarkirkan motornya di samping tenda. Aku lantas membayar wedang jaheku yang sudah habis tak bersisa setelah memilih beberapa nasi kucing serta dekorasinya untuk dimakan di rumah.
“Matur nuwun, ya, Mbak, sudah dilarisi. Jarang-jarang kalau hujan ada yang beli,” ujarnya dengan wajah yang sumringah. Aku hanya tersenyum, merasakan hangatnya ucapan tersebut di dalam hati.
Setelah itu, aku berpamitan dengan ibu angkringan dan laki-laki dewasa tadi seraya membungkukkan badan. Saat kutanya bagaimana cara kami berkomunikasi mengenai buku yang kucari, ia—laki-laki dewasa tadi—hanya mengajakku untuk sering-sering mampir kemari. Katanya, ia akan menitipkan buku itu pada ibu angkringan jika kami tidak sempat bertemu. Aku hanya mengangguk mengiyakan, berterima kasih banyak-banyak sebelum meninggalkan angkringan.
Oh, iya. Perihal bantal leher bermotif panda yang kugunakan sebagai bantal duduk, katanya sebaiknya kubawa saja sebagai bekal ketika bepergian. Aku hendak melemparkan bantal itu kepadanya saat ia menambahkan, “agar bisulannya tidak menular pada saya.”, namun kutahan dengan tatapan super tajam meski dibalas tawa olehnya.
Sore itu, sebelum pukul lima sore, akhirnya aku bisa melintasi Jalan Bantul dengan perasaan lega. Tanpa aku sadari sebelumnya, ternyata hujan tidak selalu membawa suasana menjadi biru. Terkadang, bertemu dengan manusia, menjalin percakapan macam-macam, lalu membawanya bahagia bukan hal yang rumit untuk dilakukan dan bisa membantu energi kita terisi. Begitulah.